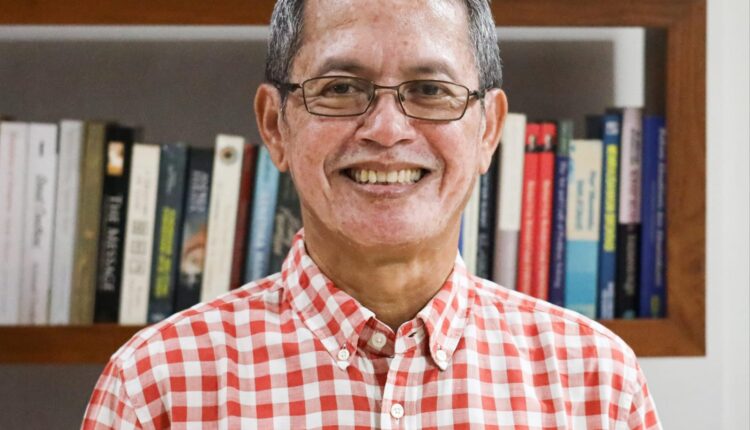Tarif Turun, Petani Terimpit: Saatnya Kita Beli dari Negeri Sendiri
Oleh Agus Somamihardja, Ph.D., alumnus Asian Institute of Technology (AIT) Thailand dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Pemerintah menyambut gembira keputusan Presiden AS Donald Trump menurunkan tarif impor produk Indonesia dari 32% menjadi 19%.
Disebut sebagai “kemenangan diplomasi dagang”. Tapi seperti biasa, rakyat kecil tak ikut merayakan.
Di balik angka yang tampak menguntungkan, tersembunyi jebakan lama: pasar dibuka lebar, petani jadi korban.
Karena, pada saat yang sama, barang dari AS termasuk pangan dan produk manufaktur, masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai tarif impor alias tarif nol persen.
Menurut pengumuman resmi, perjanjian ini memberikan akses penuh bagi eksportir AS, tanpa persyaratan tarif timbal balik dari Indonesia.
Tampaknya seimbang. Tapi mari kita lihat lebih dalam: produk-produk pertanian dari AS seperti gandum, kedelai, jagung, daging, dan susu, masuk dengan harga sangat murah.
Sementara petani kita berproduksi sendiri dengan beban tinggi dan dukungan minim.
Ini bukan perdagangan bebas. Ini adalah perdagangan tidak adil. Kesepakatan ini berpotensi memperparah ketergantungan pangan nasional.
Hingga kini, Indonesia masih tergolong sebagai salah satu negara pengimpor pangan terbesar di dunia.
Data BPS tahun 2024 mencatat sekitar 2,7 juta ton kedelai dan 11 juta ton gandum masuk ke Indonesia tiap tahun, mayoritas berasal dari Amerika Serikat, Brasil, dan Australia.
Kedelai digunakan untuk tempe, tahu, kecap, dan bungkil kedelai untuk pakan ternak.
Sementara gandum menjadi bahan utama tepung terigu untuk konsumsi harian masyarakat.
Menurut FAO 2023, negara-negara yang mengandalkan lebih dari 60% pangan dari impor termasuk dalam kategori ‘rentan pangan akut’, terutama dalam menghadapi krisis global.
Jika arus barang dari AS makin deras tanpa kontrol (tarif nol persen), petani lokal akan semakin kehilangan insentif untuk bertani.
Produk impor yang datang dengan harga murah akibat subsidi negara asal akan terus menekan harga pasar domestik.
Dalam posisi ini, petani lokal dipaksa bersaing secara tidak adil di pasar yang dibuka lebar tanpa perlindungan.
Banyak yang akhirnya menyerah, meninggalkan ladang, atau beralih ke pekerjaan lain.
Dijajah Lewat Piring Makan
Menurut OECD–WTO (2022), AS dan Eropa masih aktif mensubsidi ekspor pangan. Artinya, produk mereka dijual ke luar negeri dengan harga artifisial.
Ini merusak harga dan membunuh daya saing petani negara berkembang. Indonesia perlahan kehilangan kendali atas pangan: atas harga, pasokan, bahkan masa depan petani sendiri.
OECD–WTO (2022) mencatat bahwa subsidi ekspor pertanian di negara maju mencapai USD 228 miliar, dan lebih dari separuhnya digunakan untuk mendorong ekspor surplus ke negara berkembang.
Akibatnya jelas: Indonesia tak lagi menjadi produsen utama pangan untuk rakyatnya sendiri.
Kita berubah menjadi pasar abadi bagi limpahan surplus pangan negara lain. Kita kehilangan kendali atas harga, kehilangan kendali atas pasokan, dan perlahan-lahan kehilangan masa depan petani kita sendiri.
Ketahanan pangan nasional dipertaruhkan di meja dagang internasional.
Padahal, konstitusi dan undang-undang kita tegas berbicara. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 14 menyatakan: “Kemandirian pangan dilaksanakan berdasarkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara berkelanjutan.”
Tapi apa daya, semangat pasal ini dikhianati oleh kebijakan yang lebih mementingkan impor murah daripada pemberdayaan petani sendiri.
Kita bukan hanya dijajah di ladang, tapi juga di piring makan.
Menuju Negara Gagal
Dengan membiarkan pangan lokal kalah bersaing di tanahnya sendiri, negara sedang melanggar amanat hukum dan mengabaikan kebutuhan strategis masa depan.
Lebih dari itu, pemerintah sedang mengekalkan bentuk kolonialisme gaya baru.
Kita menjual bahan mentah (nikel, batu bara, sawit) dan membeli barang jadi (pesawat, kedelai, daging, jagung), dengan nilai tukar yang tak pernah setara.
Di mana rakyat? Petani dan produsen kecil tak diwakili dalam meja perundingan. Tapi mereka yang paling merasakan dampaknya.
Harga jatuh, pasar hilang, dan kepercayaan untuk terus bertani makin memudar.
Faktanya, pemerintah memang mengabaikan rakyat banyak, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Alih-alih membela petani, nelayan, dan produsen pangan lokal, perjanjian dagang seperti ini justru lebih mencerminkan keberpihakan pada elite dagang dan pemilik modal besar.
Masa depan Indonesia tidak bergantung pada diplomasi ekspor atau angka surplus, tapi pada kemampuan bangsa ini menghidupi dirinya sendiri.
Kita tidak kejar skor ekspor, tapi jaga nyawa dapur rakyat. Yang dibutuhkan bukan retorika swasembada, tapi kebijakan nyata yang melindungi dan menumbuhkan pangan lokal di pasar sendiri, pasar yang adil bagi hasil bumi anak negeri.
Pemerintah kembali mengabaikan kepentingan rakyat. Keputusan-keputusan besar dibuat jauh dari kehidupan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang justru menopang kebutuhan bangsa. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi tanda kemunduran arah bernegara.
Daron Acemoglu dan James A. Robinson dalam bukunya Why Nations Fail (2012) mengingatkan, jika ekonomi dan politik dikuasai segelintir elite tanpa kontrol rakyat, maka negara sedang menuju kegagalan.
Sayangnya, Indonesia kini tampak berjalan ke arah itu. Pembangunan hanya jadi alat mempertahankan kekuasaan, bukan untuk memerdekakan rakyat.
Bagaimana jalan keluarnya? Semua ada di kita. Setidaknya, ada tiga hal yang bisa kita lakukan.
Pertama, pemerintah mesti segera menyusun mekanisme proteksi cerdas: tarif masuk selektif untuk produk pangan strategis yang bisa diproduksi lokal, harga dasar pembelian hasil tani, dan anggaran untuk menyerap hasil petani.
Kedua, koperasi petani harus diperkuat agar bisa menjadi agregator dan offtaker bukan hanya menunggu proyek.
Hilirisasi pangan rakyat harus didorong: aneka kacang lokal seperti koro pedang menjadi tempe lokal, jagung menjadi sereal, gula aren menjadi pemanis sehat.
Ketiga, yang terpenting: konsumen Indonesia harus mulai sadar. Kita harus memilih membeli hasil bumi negeri sendiri.
Kita perlu warung, pasar, dan e-commerce yang berpihak pada produk lokal.
Kita harus mulai membangun kebiasaan makan dari petani sendiri, bukan dari kapal kontainer asing.
Konsolidasi Ekonomi Rakyat
Pemerintah bisa salah jalan. Tapi, bangsa harus tetap berjalan dengan arah yang benar sesuai dengan tujuan dan cita cita kemerdekaan.
Maka, jika kesepakatan dagang ini hanya didasari kepentingan pemerintah jangka pendek, maka hanya elite dagang dan pemilik modal yang bisa tersenyum. Maka, masyarakat harus tetap mengawal dengan cerdas dan adil.
Ini bisa menjadi momentum konsolidasi ekonomi rakyat. Tugas kita bukan sekadar menuntut tarif murah, tapi menegakkan keberpihakan pada petani, pada bumi sendiri. Karena pangan adalah soal kemerdekaan. (*)