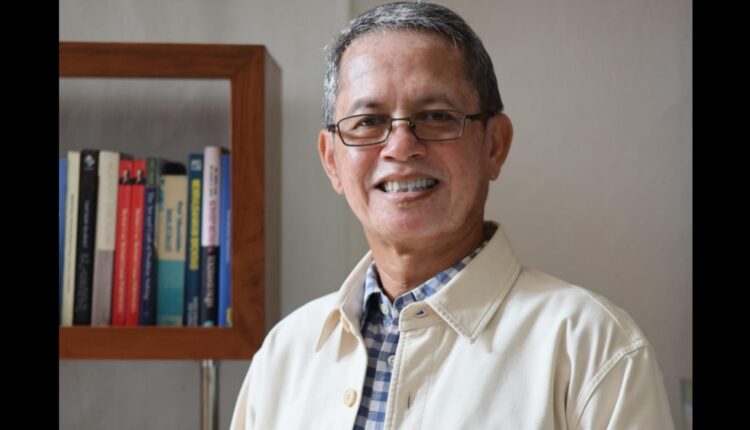Stigma Anarko dan Kepengecutan Kekuasaan
Oleh Agus Somamihardja, Alumnus Asian Institute of Technology (AIT) Thailand dan Institut Pertanian Bogor (IPB)
Jakarta- Beberapa hari ini jalanan kembali diriuhkan oleh teriakan suara rakyat. Dari depan DPR hingga simpang kota, tuntutan bergema: hapus outsourcing, hentikan PHK, hentikan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Keresahan publik itu bahkan berkembang menjadi seruan lebih tegas: bubarkan DPR. Lembaga yang seharusnya mewakili rakyat kini dirasa makin jauh dari amanah yang diembannya. Mereka larut dalam pesta kekuasaan, tidak peduli derita rakyat yang kian berat.
Tunjangan, fasilitas, dan kemewahan hidup para anggota dewan bagaikan langit dan bumi dibandingkan dengan kesusahan rakyat yang antre beras murah atau kehilangan pekerjaan.
Kontras inilah yang melahirkan rasa muak. Gedung DPR bukan lagi rumah rakyat, melainkan menara gading yang hanya berpihak pada segelintir elite.
Rakyat melakukan demo karena keresahan begitu dalam. Mereka merasa dikhianati para penyelenggara negara. Trias politika yang mestinya bekerja untuk saling mengawasi kini justru tampak bersekongkol.
Rakyat melihat bahwa kekayaan dan kemakmuran negeri ini seakan hanya dicipta untuk dinikmati lingkaran kecil elite. Termasuk mereka para anggota dewan yang seharusnya berdiri di pihak rakyat.
Sayangnya, keresahan rakyat sering dibungkam dengan stigma anarko. Kata ini berasal dari bahasa Yunani an-arkhos yang berarti “tanpa penguasa.”
Dalam kajian politik, anarkisme bukanlah gambaran kerusuhan atau kekacauan seperti yang sering dipropagandakan. Ia justru lahir sebagai kritik terhadap kekuasaan yang menindas.
Intinya, anarkisme adalah gagasan tentang masyarakat yang adil tanpa dominasi segelintir elite. Kebebasan individu dijaga, keputusan diambil secara sukarela, dan solidaritas sosial menjadi perekat.
Tokoh seperti Bakunin (1873) dan Kropotkin (1902) menekankan bahwa anarkisme bukan ajakan untuk merusak, melainkan upaya membangun tatanan yang lebih manusiawi dan setara.
Namun, dalam wacana populer di Indonesia, istilah ini kerap dipelintir menjadi label bagi demonstran yang dianggap perusuh.
Padahal, secara akademis kerumunan tidak selalu identik dengan kekacauan. Ia bisa menjadi wujud solidaritas, identitas kolektif, dan aspirasi rakyat untuk keadilan (Le Bon, 1895; Reicher, 1984).
Jadi, anarkisme sejati berbeda jauh dari citra kerusuhan jalanan yang kerap dipropagandakan penguasa.
Ironisnya, istilah “anarko” sering dipakai untuk menakut-nakuti rakyat yang berteriak demi keadilan.
Padahal, bila kita merenung lebih dalam, “anarko sejati” adalah mereka yang menghancurkan keadilan dengan rapi di balik jas resmi, di balik undang-undang yang dipelintir.
Mereka adalah elit yang merampok sumber daya, mengabaikan jeritan rakyat, membajak hukum demi kekuasaan dan kepuasan mereka sendiri.
Ketika aparat menggunakan stigma anarko sebagai alasan tindakan represif, keamanan yang gegabah justru melahirkan korban.
Kasus tragis Affan Kurniawan, seorang tukang ojek online, menjadi bukti pahit. Ia bukan perusuh, bukan pembuat onar. Ia hanyalah rakyat biasa yang mencari nafkah, namun pulang tinggal nama akibat aparat yang kehilangan kendali.
Belakangan, rakyat kembali dikejutkan dengan banyaknya korban sipil lain yang dianiaya polisi dalam aksi massa.
Semua ini menyingkap kenyataan pahit: anarkisme sejati bukan datang dari rakyat yang menuntut keadilan, melainkan dari kekuasaan yang menindas rakyat dengan kekerasan tanpa empati dan tanpa pertanggungjawaban.
Luapan kemarahan rakyat akhirnya meledak dalam aksi spontan: pembakaran dan penjarahan rumah anggota DPR serta menteri yang dianggap melukai hati rakyat. Padahal semua ini bisa dicegah andai para wakil rakyat dan pemerintah berani membuka ruang dialog.
Sayangnya, mereka lebih memilih bersembunyi di balik pagar kawat dan barisan aparat.
Kepengecutan untuk berhadapan dengan rakyat menjadi bukti nyata bahwa mereka sudah tidak lagi berdiri di pihak yang seharusnya mereka wakili.
Kata “anarko” mestinya lebih tepat diarahkan pada mereka yang menjadi penyebab kekacauan terselubung semacam itu. Yakni para elit yang mempreteli tatanan hukum demi kelangsungan kuasa.
Rakyat yang menuntut hak jelas bukanlah biang kerusuhan. Mereka adalah orang-orang yang sedang memperjuangkan ruang demokrasi yang makin disudutkan.
Suara keadilan adalah hak setiap warga. Menyuarakan tanpa kekerasan adalah kewajiban moral.
Jangan biarkan stigma menyamarkan legitimasi tuntutan rakyat. Ketika kita marah terhadap ketidakadilan, biarkan kemarahan itu tetap teguh mempertahankan martabat perjuangan.
Kita semua, termasuk pemerintah, harus belajar melihat kerumunan bukan sebagai ancaman.
Kerumunan adalah cermin aspirasi rakyat, wujud hidupnya demokrasi. Jika suara itu terus diberangus dengan stigma, maka yang benar-benar anarkis bukanlah rakyat, melainkan kekuasaan yang kehilangan nurani.
Kini, presiden menjanjikan bahwa aspirasi rakyat akan didengar. Jangan biarkan momentum ini hilang. Rakyat harus terus bersuara.
Inilah saat yang tepat bagi mahasiswa, akademisi, dan forum guru besar untuk tampil di depan, menghadap presiden, menyuarakan berbagai tuntutan akan keadilan.
Ini adalah kesempatan bagi generasi muda untuk memahami makna serta praktik demokrasi sejati: keberanian bicara, ketulusan membela, dan keteguhan menjaga kedaulatan rakyat.
Hanya dengan keberanian seperti ini, kita bisa memastikan bahwa demokrasi tidak lagi direduksi menjadi panggung kekuasaan semu.
Kita bisa mencegah terulangnya komplotan di antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berkhianat pada rakyat.
Dan kita bisa membangun kembali trias politika sebagai pilar penyangga demokrasi, bukan sebagai alat perampasan kedaulatan. (*)