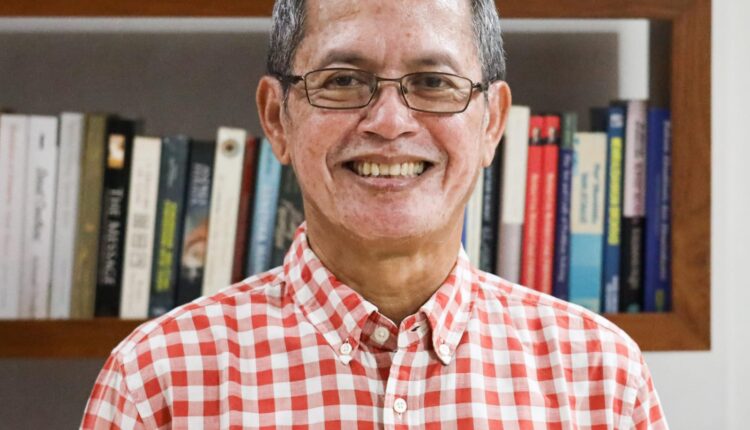Revolusi Pertanian dan Jebakan Pangan
Oleh Agus Somamihardja, Ph.D., Alumnus Asian Institute of Technology (AIT) Thailand dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens (2014), menyebut revolusi pertanian sebagai “penipuan terbesar dalam sejarah.”
Dari berburu dan meramu yang relatif bebas, manusia beralih menanam gandum dengan harapan hidup lebih stabil. Kenyataannya, justru gandum yang menundukkan manusia.
Demi menjaga tanaman tetap tumbuh, manusia harus bekerja lebih keras. Membajak, menanam, merawat, memanen dan menyimpan. Hidup menjadi penuh risiko. Gagal panen, kelaparan, dan konflik. Revolusi pertanian memang melahirkan kota dan peradaban. Tapi juga jebakan: ketimpangan dan kerja rodi.
Pola itu berulang hingga hari ini. Indonesia pun sering terjebak dalam logika “komoditas pangan penyelamat,” yang dalam praktiknya lebih banyak menguntungkan elite daripada rakyat.
Lihat saja sawit. Ia disebut emas hijau dan penyumbang devisa besar. Namun siapa yang paling untung? Korporasi raksasa pemilik jutaan hektar. Sementara petani kecil hidup dari lahan sempit. Plasma sering tersandera harga pupuk dan ketidakpastian pasar. Lingkungan rusak, rakyat desa tetap miskin.
Atau tebu. Sejak zaman kolonial, tebu dipaksa menjadi tulang punggung industri gula. Buruh tebang hidup dengan upah rendah, musiman, tanpa jaminan kesejahteraan. Negara masih impor gula jutaan ton.
Sementara, jargon “swasembada” selalu digembar-gemborkan. Lagi-lagi, yang kenyang adalah pengusaha pabrik dan importir. Bukan buruh dan petani.
Dan jangan lupa kedelai. Tempe yang kita banggakan ternyata lebih bergantung pada petani Amerika dibandingkan petani lokal. Harga tempe di warung bisa naik hanya karena cuaca di Midwest.
Petani kita pernah menanam kedelai, tapi kalah bersaing dengan banjir impor. Di sini jelas terlihat, revolusi pangan tidak selalu berarti kedaulatan. Bisa jadi justru ketergantungan.
Apa maknanya bagi kita?
Pertama, sejarah menunjukkan: kemajuan produksi pangan tidak otomatis membawa kesejahteraan rakyat. Revolusi pertanian dulu menjanjikan surplus, tapi membuat petani hidup dalam beban kerja.
Sawit, tebu, kedelai, dan gandum menjanjikan kemakmuran. Tapi kenyataannya rakyat tetap terbebani utang. Harga mahal, dan tanah yang semakin tergerus.
Kedua, kita perlu bertanya: siapa yang benar-benar untung? Apakah rakyat banyak, atau segelintir elite yang menguasai lahan dan impor?
Ukuran untung-rugi sebuah bangsa bukan hanya angka ekspor dan devisa. Namun, apakah rakyatnya bisa makan dengan layak dan hidup bermartabat.
Lalu, apa jalan keluarnya? Salah satunya adalah diversifikasi pangan. Alam Nusantara kaya, iklimnya mendukung keragaman.
Mengapa kita harus menggantungkan diri pada gandum yang tidak tumbuh di tanah kita? Mengapa tempe harus terus berbahan kedelai impor? Padahal ada koro, ada kacang hijau, ada kacang gude, ada kacang tunggak, atau lamtoro yang bisa diolah sama baiknya?
Diversifikasi artinya makan apa yang tumbuh sesuai musimnya. Sesuai lingkungannya. Dari sisi gizi, itu lebih lengkap dan alami. Dari sisi suplai, itu lebih terjamin karena tidak bergantung pada impor.
Bahkan, dari sisi fisiologi, tubuh manusia lebih mudah menerima makanan yang memang sudah ratusan tahun tumbuh dan dikonsumsi di lingkungannya.
Dengan diversifikasi, rakyat tidak terikat pada satu komoditas yang mudah dimonopoli. Justru ada fleksibilitas.
Ketika harga beras naik, kita masih bisa makan singkong. Ketika kedelai langka, kita punya koro. Ketika gandum mahal, kita bisa kembali ke jagung dan sorgum.
Inilah kedaulatan pangan yang sejati. Bukan sekadar swasembada satu komoditas, tapi kebebasan untuk memilih dari kekayaan pangan lokal.
Contohnya? Masyarakat Maluku dan Papua yang bertahan dengan sagu. Atau masyarakat Jawa yang terbiasa dengan pola makan “tiga rupa”: nasi, sayur, dan lauk sederhana dari hasil pekarangan.
Semua selaras dengan musim dan lingkungan. Itulah kearifan yang membuat pangan lebih terjangkau, Gizi lebih seimbang, dan tubuh lebih sehat.
Seruan kita sederhana. Mari makan apa yang petani kita tanam. Mari tanam apa yang Masyarakat kita makan. Mari biasakan kembali pola makan yang selaras dengan musim, tanah, dan budaya kita sendiri.
Revolusi pertanian dulu menjadikan manusia tawanan gandum. Jangan biarkan bangsa ini kembali jadi tawanan sawit, tebu, atau kedelai impor.
Saatnya rakyat berdaulat atas pangan. Dan bangsa ini berdiri sebagai tuan di tanah sendiri. Program Makan Bergizi (MBG) seharusnya diarahkan untuk mendukung pola ini. Bukan sekadar pengadaan massal yang menguntungkan segelintir pengusaha.
Program MBG harus menjadi sarana diversifikasi pangan lokal. Artinya, menu MBG bisa disusun dari bahan pangan yang tumbuh di sekitar desa: singkong, jagung, sorgum, koro, ikan lokal, sayur pekarangan, buah musiman.
Dengan begitu, gizi anak-anak terpenuhi, biaya lebih efisien, Dan yang paling penting petani serta pelaku UKM di desa ikut berdaya.
Jika MBG diselaraskan dengan diversifikasi pangan, program ini tidak hanya memberi makan anak sekolah. Tetapi juga memberi kehidupan pada petani, nelayan, dan pengolah pangan di desa. Roda ekonomi bergerak dari bawah, gizi anak membaik, dan kedaulatan pangan bangsa semakin kokoh. (*)