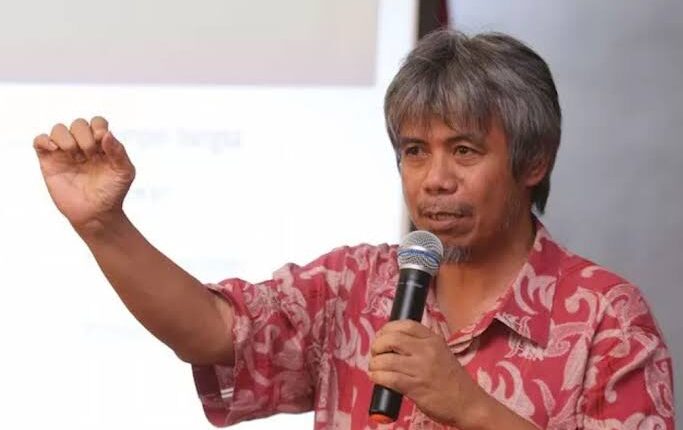Siapkan Peradaban Tanpa Energi Fosil Demi Masa Depan Anak Cucu
Oleh Yazid Bindar, Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung.
NARASI yang menyatakan bahwa dunia “tak bisa move on dari energi fosil” adalah cara pandang jangka pendek yang menenangkan sementara, tetapi membahayakan masa depan. Ia mirip orang yang berkata bahwa karena manusia masih menggunakan plastik di mana-mana, maka tak ada gunanya mengurangi produksi minyak.
Padahal, inti dari pembangunan peradaban adalah kemampuan merancang masa depan yang tidak ditentukan oleh keterbatasan hari ini. Energi fosil memang masih menyusup dalam banyak lini kehidupan modern, tetapi itu bukan alasan untuk menormalkan ketergantungan; itu justru alasan mempercepat transisi agar ketergantungan itu perlahan hilang.
Lebih jauh, penjelasan “semua masih dari fosil” sering mengaburkan fakta bahwa bahan baku adalah aspek yang berbeda dari sumber energi. Dunia bisa tetap membutuhkan kimia dasar tertentu dari minyak, tetapi tidak berarti listrik global harus terus dibakar dari batu bara atau gas.
Menyamakan bahan baku dengan kebutuhan energi adalah kekeliruan logika. Justru, transisi energi memberi ruang teknologi baru mengembangkan alternatif bahan baku, termasuk biopolimer, material berbasis selulosa, bio-komposit, dan kimia hijau. Pandangan jangka pendek membingungkan status quo sebagai keniscayaan, padahal ia hanyalah fase dalam perkembangan material dan energi umat manusia.
Ketidakabadian Fosil dan Realitas Geologis
Argumen “fosil ada di mana-mana” sering lupa pada hal paling fundamental: fosil tidak terbarukan. Ia terbentuk dari proses jutaan tahun, sementara manusia menghabiskannya dalam hitungan abad.
Secara geologis, cadangan minyak dan gas konvensional semakin tua dan semakin dalam—menuntut biaya eksplorasi yang lebih mahal, risiko yang lebih besar, dan kualitas yang lebih rendah.
Bahkan, negara-negara produsen besar mulai bersiap terhadap decline produksi internal dalam beberapa dekade. Bergantung pada sumber daya yang pasti habis adalah resep krisis jangka panjang.
Lebih dari itu, sejarah energi menunjukkan bahwa umat manusia selalu bergerak ke arah sumber energi dengan densitas lebih tinggi, efisiensi lebih besar, dan emisi lebih rendah. Batu bara menggantikan kayu, bukan karena kayu menghilang, tetapi karena ia tidak efisien untuk revolusi industri.
Minyak menggantikan batu bara bukan karena batu bara habis, tetapi karena minyak lebih fleksibel, lebih bersih, dan lebih mudah diangkut. Demikian pula energi terbarukan bergerak naik, bukan karena minyak langsung habis, tetapi karena ia secara struktural lebih kompetitif pada jangka panjang. Menolak transisi energi justru bertentangan dengan logika sejarah inovasi energi itu sendiri.
Risiko Ketergantungan Jangka Panjang
Bergantung pada energi fosil jangka panjang adalah mempertaruhkan ekonomi generasi mendatang pada komoditas global yang sangat volatil. Dari krisis minyak 1970-an hingga harga gas liar pada 2022, negara yang terlalu bergantung pada fosil menjadi rentan terhadap guncangan geopolitik dan pasar dunia.
Pemikiran jangka pendek yang menormalisasi ketergantungan ini seperti menyarankan sebuah keluarga untuk terus mengandalkan sumber pendapatan yang sebentar lagi hilang, hanya karena hari ini masih bisa digunakan.
Lebih buruk lagi, infrastruktur fosil adalah aset terdampar (stranded assets) yang risiko ekonominya semakin menumpuk. Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, hingga Amerika Serikat terus memperketat kebijakan emisi.
Artinya, proyek yang dibangun hari ini bisa tidak layak secara finansial dalam 10–15 tahun ke depan. Anak cucu kita berpotensi mewarisi infrastruktur yang mahal, tidak efisien, dan sudah tidak relevan secara teknologi.
Di satu sisi, menyebut CCS (Carbon Capture and Storage) sebagai satu-satunya penyelamat adalah tindakan yang mengalihkan risiko ekonomi itu kepada generasi mendatang, bukan menyelesaikannya.
CCS Bukan Obat Mujarab untuk Ketergantungan
CCS bermanfaat, tetapi bukan fondasi pembangunan energi masa depan. Ia berguna sebagai jembatan untuk sektor yang memang sangat sulit didekarbonisasi—semen, baja, petrokimia—bukan sebagai alasan untuk mempertahankan pembakaran fosil tak terbatas.
Menggunakan CCS sebagai dalih agar fosil tetap dominan sama seperti menggunakan ventilator untuk membenarkan terus merokok: alat itu menyelamatkan nyawa, tetapi bukan untuk mempertahankan kebiasaan buruk.
Lebih penting lagi, CCS tetap sangat mahal, intensif energi, berisiko kebocoran, dan belum terbukti layak secara komersial dalam skala global. Banyak proyek CCS di dunia gagal mencapai target penangkapan yang dijanjikan.
Menggunakan CCS sebagai pusat argumen bahwa Indonesia harus “jadi satpam karbon” justru bisa memerangkap bangsa pada model ekonomi yang mengandalkan limbah karbon negara lain. Ini bukan kedaulatan energi, melainkan ketergantungan model baru yang tidak memberi nilai tambah inovatif bagi generasi mendatang.
Jalan Panjang Menuju Kedaulatan Energi
Transisi energi bukan tentang mematikan fosil hari ini, melainkan mempercepat pembangunan teknologi yang akan membuat fosil tidak lagi diperlukan besok. Dunia sedang mengembangkan baterai generasi baru, hidrogen hijau, bioplastik, biochar, material komposit nabati, pupuk berbasis amonia hijau, serta proses kimia yang disokong tenaga surya.
Semua ini butuh waktu, investasi, dan keseriusan. Pandangan jangka pendek yang berkata “semua masih dari fosil, jadi kita harus terima” hanya akan memperlambat inovasi dan membuat Indonesia tertinggal.
Ketergantungan pada fosil juga menunda peluang besar Indonesia dari sumber energi bersih yang justru melimpah: matahari, panas bumi, biomassa, angin, arus laut, hingga hidro kecil terdesentralisasi.
Setiap penundaan berarti kehilangan pasar teknologi miliaran dolar yang sedang direbut negara-negara Asia Timur. Jika Indonesia memilih menjadi “penitipan karbon” daripada produsen teknologi bersih, maka pilihan itu bukan pembangunan jangka panjang—itu penyerahan masa depan.
Masa Depan Material Tidak Terikat Fosil
Benar bahwa banyak produk modern masih berbasis fosil: plastik, ban, komposit, tekstil, dan pupuk. Namun, itu bukan bukti bahwa alternatif tidak mungkin, melainkan bahwa kita sedang berada di fase transisi material global.
Bioplastik berbasis pati, PLA, PHA, selulosa modifikasi, serat rami, serat kenaf, serat nanokristalin, bio-komposit dari lignin, hingga pupuk hijau berbasis elektrolisis nitrogen mulai masuk pasar. Negara seperti Brasil, Tiongkok, Belanda, dan Amerika Serikat sudah mengembangkan ekosistem industri material terbarukan yang mampu menggantikan turunan minyak pada skala besar.
Pernyataan bahwa tanpa fosil dunia “harus telanjang” atau “Jawa jadi kandang sapi” adalah hiperbola retoris—bukan analisis. Transisi material selalu bertahap. Di abad ke-19 orang juga berkata tanpa batu bara dunia akan gelap gulita; di awal abad ke-20 orang mengira tanpa kuda, kota tidak akan bisa berfungsi.
Mereka semua salah. Teknologi selalu menemukan jalan ketika manusia berinvestasi di dalamnya. Menolak masa depan hanya karena keterbatasan hari ini adalah cara gagal membaca dinamika inovasi.
Moralitas Antar Generasi dan Amanah Peradaban
Pertanyaan utama yang sering tidak disentuh oleh para hardliner fosil adalah pertanyaan moral: apakah kita berhak menyerahkan bumi yang lebih panas dan lebih rapuh kepada generasi setelah kita, hanya karena hari ini kita enggan berubah?
Mengandalkan CCS sebagai “penjara CO2” sambil mempertahankan pembakaran fosil berarti memperbolehkan generasi mendatang hidup dalam dunia penuh energi mahal, sumber daya menipis, dan iklim berbahaya.
Padahal, prinsip dasar pembangunan berkelanjutan adalah memastikan anak cucu kita memiliki pilihan yang lebih luas, bukan lebih sempit.
Di sinilah logika jangka panjang menunjukkan keunggulannya. Transisi energi bukan sekadar urusan teknologi, tetapi amanah peradaban. Energi terbarukan memberi peluang bagi dunia yang tidak hanya lebih bersih, tetapi juga lebih aman, lebih stabil, dan lebih mandiri.
Ini bukan sekadar persoalan mengurangi CO2, tetapi tentang menciptakan dunia di mana energi tidak lagi menjadi sumber perang, konflik, dan kerentanan ekonomi.
Berpikir Jauh ke Depan
Kritik terhadap pandangan jangka pendek bukan berarti menolak fosil secara absolut, melainkan memahami bahwa fosil adalah sumber daya sementara. Dalam horizon 100 tahun, dunia yang masih bergantung pada fosil adalah dunia yang gagal membangun peradaban maju.
Sebaliknya, dunia yang berinvestasi pada energi terbarukan, material baru, dan ekonomi hijau adalah dunia yang menyiapkan anak cucu untuk hidup dengan lebih aman dan lebih sejahtera.
Indonesia memiliki semua modal untuk memimpin transisi ini—bukan sekadar ikut arus. Bukan menjadi “satpam karbon”, tetapi menjadi produsen teknologi bersih, pusat inovasi material hijau, eksportir energi terbarukan, dan pemilik industri strategis yang tahan masa depan.
Inilah visi jangka panjang yang mestinya kita perebutkan, bukan retorika bahwa dunia “tak bisa move on” dari fosil. Justru tugas generasi kita adalah memastikan dunia bisa move on—dan memastikan anak cucu mewarisi dunia yang lebih layak huni daripada yang kita tempati hari ini.